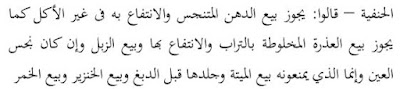Poligami yang seringkali dianggap bertentangan dengan feminisme, akan tetapi oleh masyarakat malah dianggap sebagai solusi problema sosial yang mendapat legitimasi agama.
Trend mutakhir dari perkembangan sosial masyarakat saat ini adalah menuntut dan mempertanyakan kembali segala bentuk tradisi dan aturan agama yang semakin hari dianggap tidak sesuai dengan masa kekinian. Kecenderungan ini tidaklah perlu ditakuti, bahkan hal ini adalah indikasi positif sosial, bahwa masyarakat benar-benar ingin menjalankan tatanan sosial dan tradisi berdasarkan logika dan nalar yang jernih. Islam sebagai agama yang fleksibel yang tercermin dalam al-Quran dan sunah, menyambut hangat reaksi sosial ini. Diantara kajian yang hangat dan kontroversial saat ini, adalah poligami. Meskipun polemik tentang poligami tidak bisa dikatakan sebagai hal yang baru, akan tetapi karena pembahasan ini sensitif khususnya bagi kaum hawa sehingga topik ini selalu menarik minta halayak.
Poligami yang seringkali dianggap bertentangan dengan feminisme, akan tetapi oleh masyarakat malah dianggap sebagai solusi problema sosial yang mendapat legitimasi agama. Bahkan, figur manusia suci Rasulullah Saww sendiri melakukan norma tersebut. Jelas, konsekwensi dari segala perbuatan Rasulullah saww selalu dianggap sebagai sunah untuk ummatnya. Memang terlalu sederhana memandang poligami dari sisi hukum fiqih. Bahwa hukum fiqih lebih cenderung kering apabila tidak diimbuhkan dengan nilai-nilai akhlak.
Dari satu pihak, saya sependapat dengan Faqihudin Abdul Qodir, bahwa ungkapan "poligami itu sunnah" sering digunakan sebagai pembenaran poligami, sehingga lebih cenderung kaku dalam melihat hukum tersebut, tanpa melihat latar belakang sunnahnya poligami Rasulullah Saww. Akan tetapi dari sisi lain, pendapat yang mengatakan bahwa poligami sama sekali tidak benar dan bertentangan naluri manusia, khususnya wanita adalah pikiran yang dangkal.
Allamah Thabathabai seorang filosof dan mufasir kontemporer, dalam bukunya Maqalot secara jelas menyinggung bahwa pernyataan poligami bertentangan dengan naluri wanita sebagai manusia adalah tidak benar, karena yang menjadi istri kedua juga wanita yang dengan senang hati melakukannya. Seandainya bertentangan dengan naluri wanita, maka tidak akan ada wanita yang bersedia menjadi istri kedua.
Kecenderungan para sarjana Islam yang hanya memandang dari satu sisi diantara doktrinasi tersebut menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut. Seperti kajian poligami yang mempunyai aspek murni kajian akhlak dan sosial, kemudian dipaksakan sebagai wacana yang beraspek fiqih. Ayatullah Muhammad Husein Madzohiri, guru akhlak tersohor, dan juga dikenal sebagai pakar fiqih, menyatakan bahwa kajian poligami yang berkembang saat ini adalah murni kajian akhlak dan sosial, bukan fiqih.
Dalam bukunya "Akhlok dar Khoneh" Ayatullah Husein Madzohiri mengklasifikasi poligami menjadi beberapa tipe. Pertama, poligami darurat, bahwa kondisi menuntut untuk berpoligami. Sebagai contoh, apabila istri sakit, sehingga tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri, maka suami terpaksa berpoligami. Dan bentuk poligami inilah yang mendapatkan perhatian khusus hadis-hadis Rasulullah saw. Contoh lain, adalah istri yang mandul dan suami-istri menginginkan kehadiran seorang bayi, maka suami terpaksa berpoligami. Berkenaan dengan bentuk poligami ini, Ayatullah Husein Madhohiri menganjurkan, supaya istrinya yang mencarikan istri keduanya yang sesuai dengan kondisi spritualnya. Kedua, poligami dengan motif birahi, bahwa suami membayangkan istri kedua akan memberikan kenikmatan seks yang berbeda. Yang jelas, seorang yang bertumpu kepada hawa nafsu tidak cukup beristri satu, bahkan apabila memungkinkan akan membangun lokalisasi pribadi.
Menurut sudut pandang akhlak, bentuk poligami yang kedua ini sangat berbahaya sekali. Karena mengikuti hawa nafsu seks akan menjebaknya di lembah marabahaya. Bahwa hawa nafsu seks tidak mempunyai batas akhir, yakni seseorang tidak akan pernah klimaks dan puas, sehingga orang yang terjebak didalamnya akan selalu menkonsentrasikan pikirannya demi tujuan-tujuan tersebut. Naluri seks juga akan mengalami krisis, yang biasa disebut dengan istilah "haus seks".
Ayatullah Husein Madzohiri secara jelas dalam bukunya "akhlok dar khoneh" menyatakan bahwa naluri seks yang merupakan pemberian Tuhan akan mengalami haus seks, disaat istrinya tidak dapat menjaga "iffah" (kehormatan). Wanita yang tidak menjaga kehormatannya adalah wanita yang tidak menjaga tatanan agama, sebagai contohnya, wanita yang tidak menjaga auratnya.
Didalam sejarah banyak contoh tipe poligami kedua ini, seperti yang telah menjadi kebiasaan para penguasa di masa kedigjayaan rezim Bani Umayah dan rezim Bani Abbas, yang hampir-hampir setiap dari mereka memiliki lokalisasi pribadi untuk melampiaskan hawa nafsunya. Semua ini adalah bukti ketidakpuasan individu, yang berangkat dari tidak terhormatnya istri disampingnya.
Ayatullah Husein Madzohiri juga menambahkan, bahwa kondisi haus seks tidak hanya dialami oleh laki-laki saja, tapi juga wanita. Indikasi ini dapat dilihat ketika wanita tidak menjaga auratnya, seperti memperlihatkan bagian-bagian sensitif kepada yang bukan mahramnya. Beliau juga mengingatkan, bahwa poligami jenis kedua ini sama sekali mengabaikan kesetiaan istri pertama, dan juga langkah yang salah.
Dalam buku tersebut beliau membawakan cerita seorang ulama besar dari Najaf yang mempunyai penghormatan khusus dikalangan komunitas pelajar agama, karena akhlak yang mulia dan ketakwaannya yang tinggi. Beliau adalah almarhum Sayid Ibrahim Ghozweini. Pada suatu hari, putri raja Fatah Ali Shah yang bernama Dziya'u Sulthonah telah bercerai dengan suaminya di umur yang relatif masih muda. Setelah perceraian, putri ini tidak ingin kembali ke Iran, tapi memilih hidup di kota Karbala.
Putri ini setelah beberapa lama hidup tanpa didampingi suami, tiba-tiba mengutus seseorang untuk menemui Sayid Ibrahim Ghozweini, dan mengatakan, "Aku ingin sekali, tangan anda menyentuh kepalaku, oleh karenanya aku berharap anda dapat menikahiku". Beliau menjawab, "Sampaikan salam kepada Dziya'u Sulthonah dan katakanlah, Aku tidak sesuai dengan anda, dan juga tidak kufu (istilah fiqih yang menjelaskan ketidaksesuaian) karena aku tua, sedangkan anda masih muda. Anda juga anak raja, sedangkan aku seorang pelajar agama. Dan anda juga juragan sedangkan aku miskin".
Pada hari berikutnya sampailah pesan putri yang menyatakan, "Aku bangga menjadi istri anda. Aku bangga tangan anda berada diatas kepalaku, yang artinya aku adalah istri anda. Masalah uang, aku tidak akan mengharap apa-apa dari anda, bahkan aku juga bersedia membiayai kebutuhan rumah istri pertama".
Melihat kondisi ini, yang mana sang putri sepertinya tidak akan melepaskannya, tiba-tiba Sayid Ghozweini berwudzu' (seakan beliau mencari ketenangan dengan bersuci melalui wudzu) dan menjawab yang kedua kalinya. "Sampaikan salam kepada Dziya'u Sulthonah dan sampaikan kepadanya, Bahwa aku mempunyai istri yang selama 40 tahun telah menanggung kefakiranku, dan juga menerima hidup dalam perantauan, sekaligus menanggung masa-masa susah dan setelah 40 tahun yang masih berkhidmat di rumah, melakukan tugas rumah tangga, melahirkan anak-anak, dan melayani suami, yang keseluruhannya dilakukan dalam kondisi berat dan pahit. Kemudian setelah itu, aku menikah dengan anda. Ini benar-benar menyakiti kesetiaan istri saya. Oleh karena itu, aku tidak rela menikahi anda".
Cerita ini sangat menarik sekali, sekalipun Sayid Ghozweini mempunyai idealisme yang tinggi, tapi tetap menghiraukan masalah yang seringkali dianggap remeh. Ternyata idealisme beliau tidak menghalangi kesetiaannya terhadap istrinya. Beliau sangat merendah dan tidak segan-segan menyatakan bahwa istrinya telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupannya.
Ayatullah Madzohiri setelah membawakan cerita ini, menganjurkan lebih baik biaya untuk berpoligami dihadiahkan kepada generasi muda yang berhalangan menikah karena kendala ekonomi. Beliau dalam buku tersebut juga menukil hadis Imam Musa al Kadzim As bersabda, "Seandainya aku dapat mengelola satu keluarga saja dalam satu minggu itu lebih baik bagiku dari 40 kali berhaji".
Bentuk ketiga, poligami kejiwaan, bahwa manusia memiliki kecenderungan yang terkadang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Dalam istilah ilmu psikologi disebut kecenderungan dibawah alam sadar. Pakar psikologi menyebutkan, ketika kondisi alam sadar berubah menjadi alam dibawah sadar, saat itu kondisi kejiwaan muncul. Kondisi kejiwaan sangat berbahaya sekali, karena telah kehilangan kontrol diri. Kondisi semacam ini akan muncul karena tekanan terus menerus.
Sebagai contoh, seorang istri yang kurang bisa menyambut suaminya ketika masuk rumah, yang mustinya harus menyambut dengan hangat, tapi malah menampakkan muka masam. Hari berikutnya, mengangkat suara tinggi dihadapan suaminya, sambil memerintah untuk membawa anak-anaknya yang terus mengganggu. Dan hari ketiga, meminta baju mahal yang suami tidak dapat membelinya. Semakin hari terus-menerus mendapat tekanan, sehingga suami merasa terbebani, akhirnya berfikir untuk berpoligami dengan harapan istri kedua akan memberikan ketentraman. Dan suami juga tetap akan melakukan hal yang sama, ketika mendapatkan kondisi yang sama pada istri kedua, yang akhirnya, suami akan mengambil istri yang ketiga.
Ayatullah Madzohiri dalam menerangkan poligami tipe ketiga ini, beliau menyalahkan pihak istri yang tidak dapat melayani suaminya dengan baik, dan juga tidak menjalankan sesuai dengan tuntunan agama.
Dalam memberikan gambaran dari pernikahan poligami jenis ketiga Beliau menukil sebuah cerita suami istri tauladan yang terjadi di zaman Rasulullah Saw. Seorang wanita Anshor (penduduk Madinah) yang bernama Ummu Salim yang mempunyai suami seorang pekerja. Keduanya adalah murid setia Rasulullah Saww yang masing-masing menjalankan tugas kekeluargaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saww. Mereka hanya mempunyai satu anak yang berumur dua tahun yang sangat disayangi.
Pada suatu saat, anak tersebut mengalami sakit berat dan akhirnya meninggal dunia. Istri tidak dapat menahan isak tangis, kemudian sadar bahwa suaminya akan datang dari kerja. Istri tidak ingin suaminya mengalami kegoncangan setelah bekerja seharian. Istri kemudian menyembunyikan anaknya, dan berusaha keras untuk tabah dan menghilangkan kesan sedih, sehingga ketika suami datang tidak akan curiga dengan apa yang sedang terjadi. Suamipun datang, dan disambut dengan hangat, senyum dan melayani suaminya dengan baik, seperti hari-hari biasa. Suami menanyakan kondisi anak, spontan istri menjawab: "Anak dalam kondisi sehat wal afiat". Istripun tidak berbohong, karena anak tersebut telah pergi ke surga dan telah mendapatkan ketenangan sepenuhnya.
Setelah melayani suaminya dengan baik dan dan juga nampak wajah letihnya telah hilang, kemudian sang istri bertanya kepada suaminya, "Apabila seseorang menitipkan amanat kepada kita, kemudian setelah beberapa lama amanat tersebut diminta kembali, apakah kita berhak gusar dengan mengembalikan amanat tersebut kepada pemilik aslinya?" Suami spontan menjawab, "Tidak selayaknya demikian, karena berkhianat dengan amanat adalah dosa besar, maka kita harus mengembalikan amanat tersebut".
Kemudian istri melanjutkan pembicaraannya, "Kalau memang demikian, beberapa tahun yang lalu, Allah swt telah memberikan amanat kepada kita. Dan amanat tersebut telah kembali kepada pemilik aslinya, bahwa sebenarnya anak kami telah meninggal dunia". Suami mendengar berita ini, malah mengucapkan puji syukur kepada Allah swt. Memang, sewajarnya suami mensyukurinya, karena telah mendapatkan istri yang punya pengertian tinggi dalam kondisi yang gawat.
Setelah menimbang latar belakang poligami yang terbagi menjadi tiga tipe diatas, maka saatnya untuk mempertanyakan latar belakang poligami Rasulullah saww. Kenapa Rasulullah merasa cukup dengan Sayyidah Khodijah binti Khuwailid? Jawabannya sangat jelas, karena Rasulullah saww merasa tidak perlu berpoligami dengan kehadiran Sayyidah Khodijah yang sangat mewakili dalam segala aspek.
Maka tidak heran, apabila Rasulullah saww sering memuji-muji beliau dihadapan istri yang lain. Sehingga terkadang pujian Rasulullah saww kepada beliau menimbulkan kecemburuan bagi istri-istri yang tidak sadar dengan kebesaran Sayyidah Khodijah. Kemudian dari sisi lain, dapat ditambahkan, bahwa kenapa Rasulullah saww sepeninggal Sayyidah Khodijah baru berpoligami? Apakah istri yang ada tidak dapat mendampinginya dengan baik?
Untuk menelaah pertanyaan berikut ini, terlebih dahulu harus melihat latar belakang historis di masa itu. Bahwa sejarah membuktikan kepedulian lebih Rasullullah saww kepada anak-anak yatim dan keluarga syuhada peperangan mendorong Rasulullah saww untuk berpoligami, sehingga dapat memberikan perhatian lebih kepada mereka. Mungkin sebagian orang akan bertanya, "Kenapa solusinya harus menikahi ibu anak-anak yatim tersebut? Bahwa kondisi saat itu menuntut Rasulullah harus menikahinya, karena tanpanya tidak akan terealisasi sikap perhatian beliau saww.
Kondisi pada saat itu, dapat dilihat dengan rumah dan ruangan yang terbatas para keluarga syuhada'. Ini dapat dijadikan alasan poligami Rasulullah Saww, karena berada dalam satu ruangan dengan wanita yang bukan mahramnya adalah perbuatan yang tercela, yang mana tidak sesuai dengan kapasitas sebagai Rasulullah saww. Insyaallah, analisa pendek ini dapat dijadikan sebagai bentuk pertimbangan analisa sejarah, sebelum kita terjebak pada sikap yang lebih berani dalam memandang figur suci Rasulullah saww.
Satu hal lagi yang mendapatkan perhatian lebih akhir-akhir ini dalam kajian poligami, adalah hadis kontroversial Rasulullah syang tidak setuju dengan sikap menantunya yang akan menikahi wanita lain. Pada suatu saat, Nabi saww marah besar ketika mendengar putri beliau, Fathimah binti Muhammad saww, akan dipoligami Ali bin Abi Thalib as. Ketika mendengar rencana itu, Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru, "Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib".
Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku." (Jâmi' al-Ushûl, juz XII, 162, nomor hadis: 9026).
Pakar sejarah Hasyim Ma'ruf al-Husaini dalam kitabnya Sirotul A'immah Istna Asyar secara jelas dan tegas menolak hadis tersebut, dengan menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang mursalah, bahwa kevalidan hadis tersebut diragukan. Terlebih para perawi (yang meriwayatkan hadis) juga menyebutkan bahwa wanita yang akan dikawini oleh Imam Ali As adalah Juwairiyah binti Abi Jahal Ammar bin Hisyam al-Makhzumi.
Keraguan hadis ini dapat dilihat dari riwayat yang mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sebelum kelahiran Hasan as, putra pertama Sayyidah Fathimah az-Zahra as, berarti sekitar tahun ketiga sebelum hijrah. Sedangkan tahun itu adalah tahun-tahun dimana Rasulullah saww ditekan oleh kelompok Quraisy. Dan Abu jahal adalah tokoh mereka yang sangat getol menyingkirkan Rasulullah saww, dan juga termasuk orang-orang yang mengumpulkan para kabilah dan membagi kerja setiap dari mereka untuk membunuh Nabi saww di malam hijrahnya, sehingga setiap kabilah yang ada mempunyai saham dalam membunuh Nabi saww.
Para pakar sejarah juga sepakat bahwa Abu Jahal mati di peperangan badar, kemudian keluarganya tetap bertahan dalam kondisi musyrik hingga fathu Makkah (pembebasan kota Makkah ) pada tahun kedelapan setelah hijrah. Dengan kondisi politik pada saat itu, bagaimana mungkin Abu Jahal datang kepada Rasulullah saww meminta izin untuk menikahkan putrinya kepada Imam Ali as. Apalagi diceritakan dalam hadis tersebut, Rasulullah datang ke masjid dan naik mimbar. Sedangkan masjid pertama kali berdiri di Madinah, dan tahun ketiga sebelum hijrah tidak ada masjid untuk kaum muslimin, terlebih pada waktu itu adalah dakwah pertama Rasulullah saww.
Sangat jelas sekali keganjalan hadis ini. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil ketidaklegalan poligami dan sikap Nabi saww yang anti poligami. Poligami tetap sebagai solusi sosial dan mendapat legitimasi dari syariat. Tapi tidak berarti bahwa semua bentuk poligami itu sunnah dan mendapat dukungan penuh dari agama. Tapi dalam kondisi tertentu, poligami juga dapat dikatakan sebagai sunnahnya. Sunnah dan tidaknya poligami, tergantung pada bentuk poligami dan motif berpoligami.